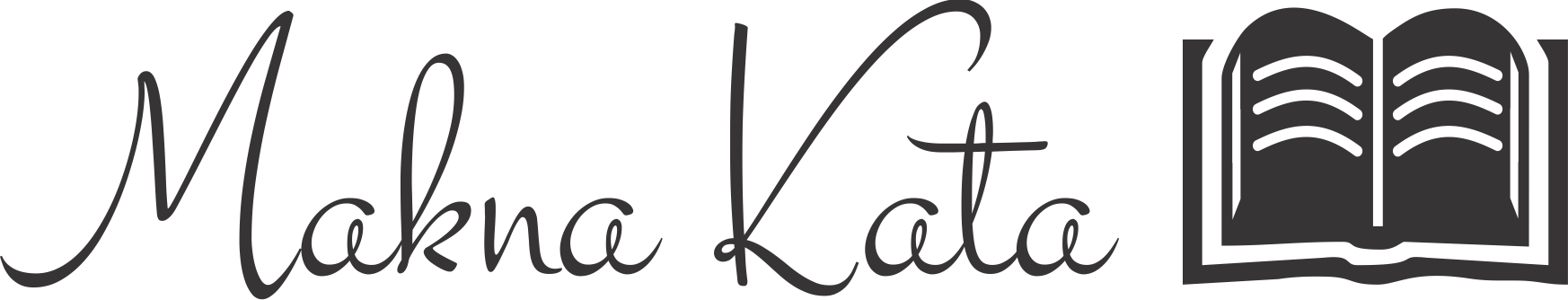Aku terbangun pada suatu hari yang panas. Aku membuka mata dan merasakan sinar matahari masuk dari jendela tanpa basa-basi menusuk mataku. Dalam posisi terlentang begini, aku dapat memandang langit yang dibingkai dahan-dahan pohon tanpa daun. Aku harap langit masih biru. Warnanya tidak terpancar dari balik kaca jendelaku yang penuh debu. Aku bergolek sedikit dan mengulet, sendi-sendi pinggangku berbunyi. Punggungku basah karena keringat, merembes ke baju sampai seprei. Semoga tidak merembes ke kasur. Aku merasa sangat kehausan. Tenggorokanku sangat kering seperti habis bernyanyi di karaoke semaleman. Mungkin aku tidur terlalu lama sehingga tubuhku sangat dehidrasi. Bahkan aku tidak ingin buang air kecil. Sembari menunggu keringat kering, aku duduk di sofa carut marut, meminum bir kaleng murahan yang aku beli di supermarket. Tangan kananku memainkan gawai. Oh ini hari Minggu, pantas saja bos tidak menelfonku. Aku lempar gawai ke ujung sofa dan menenggak habis bir sebelum suhunya semakin meningkat seperti ruangan ini.
Mungkin sudah waktunya mandi. Aku berhenti sejenak di depan pintu kamar mandi. Melihat ke langit-langit yang sudah bolong sana-sini, aku mencari tanda-tanda keberadaan kecoa. Aku menyapu seluruh pandangan ke lantai, siapa tahu kecoa bersembunyi di balik warna keramik merah marun. Berbekal semprotan serangga, aku mulai membanjur tubuhku dengan air dingin. Segar sekali rasanya setiap aliran air menyapa bagian lekuk tubuhku. Aku menggunakan sabun cair untuk membersihkan kotoran yang menempel pada lipatan-lipatan leher, ketiak, punggung, selangkangan, belakang lutut, dan sela-sela jari kaki. Aku gosok-gosokkan seluruh tubuhku, yang kadang aku terlalu bersemangat, sehingga kulitku menjadi merah-merah karena terlalu keras digosok. Tiba-tiba aku merasakan kaki-kaki kecil merayap pada punggung kakiku. “Sialan! Kecoa sialan!” Aku hentakkan kakiku dan kecoa itu jatuh ke lantai. Terlihat dia hendak mengepakkan sayapnya. Dengan sigap aku semprotkan pembasmi serangga itu tepat di tubuh cokelatnya. Kecoa itu masih berlari sana-sini, berusaha memanjat dinding namun terjatuh, terbalik, tak bisa membalikkan diri lagi. Kaki-kaki kecilnya meronta-ronta minta tolong, namun siapa yang mau menolong? Aku semprotkan sekali lagi, kaki-kaki itu mulai melambatkan rontanya. Aku menahan nafas dan sesekali nafas dari mulut, sambil melanjutkan menyiram tubuhku yang masih penuh busa sabun.
Aku merasa paling cantik kalau sudah mandi. Aneh ya, padahal mandi tidak ada hubungannya dengan memancungkan ujung hidungmu, memperbesar lekuk matamu, mempertebal bibirmu, atau membuat dagumu menjadi lancip. Morfologi wajahmu akan tetap sama. Wajahku tetap tembam, berahang kuat, berhidung jambu, bermata kecil. Bibirku memang sudah tebal, tapi tidak cantik. Orang tetap akan mengenalimu sebagai kamu walaupun sudah mandi. Bayangkan jika setiap kali mandi, kita menjadi cantik sampai tidak dikenali. Setiap kali mandi, identitat kita berganti. Pagi menjadi si A, malam menjadi si B. Besok paginya menjadi si C. Kita harus berkenalan lagi dengan orang bahkan orang serumah! “Iya ini aku, tadinya aku A, tetapi aku sekarang menjadi B.” Aku tertawa-tawa sendiri melihat diriku berbicara di depan cermin. Tetapi aku tetap merasa paling cantik, mungkin karena sudah wangi dan tidak bau keringat lagi. Kecantikan sering disimbolkan dengan bunga. Bunga membuat cantik sebuah rumah bahkan sampai sebuah makam. Bunga menghiasi dengan warna warninya. Perpaduan kembang tabur, mawar merah, mawar putih, serta anggunnya melati. Tak kalah juga, bunga mempunyai kekuatan untuk menghiasi makam dengan berbagai wewangian yang entah bagaimana bisa bersatu padu menjadi wangi khas pemakaman. Wangi bunga seakan-akan ingin mengusir bau mayat yang ditanamkan dalam-dalam di tempat itu. Setiap berkunjung, peziarah tetap menabur bunga walaupun mayat dikuburkan sudah bertahun-tahun yang lalu.
***
“Mbah, aku janji akan menjadi orang yang membanggakanmu, walaupun entah Mbah bisa melihatku atau tidak dari balik tanah ini.” Aku selalu berjanji dalam hati di depan makam Mbah Kakung setiap kali berkunjung saat lebaran. Mama duduk disamping makam, meneteskan airmata. Matanya menatap nisan yang kini sudah diganti menjadi batu marmer. Papa duduk pada sisi makam yang lain, merokok, dan memainkan gawai. Mataku tertuju pada bunga mawar yang diletakkan dibawah nisan. Tiga bunga mawar merah diletakkan menghiasi helm besi perak yang memantulkan sinar matahari pada siang hari itu. “Bunga mawar merah adalah bunga kesukaan Mbah Kakung.” Begitu lah kata Mama. Aku sendiri tidak pernah bertemu Mbah Kakung semasa hidupnya. Menurut penuturan Mama, Mbah Kakung orang yang sangat jujur. “Dulu Mbah Kakung pernah ditawari untuk naik pangkat, jadi jenderal. Siapa yang nggak mau jadi jenderal? Ya Mbah Kakung itu. Disuruh bayar katanya, ya buat apa toh? Pangkat kok dibeli. Yaudah jadi Kolonel aja, yang penting sudah berjuang membantu kemerdekaan Indonesia.” Aku membayangkan betapa kuat pendirian Mbah Kakung. Susah sekali pasti menjadi Mbah Kakung pada saat itu, apalagi pada saat-saat seperti sekarang ini. Aku menebak-nebak Mbah Kakung sepertinya tidak mempunyai banyak teman. “Mbah Kakung itu juga nggak mau ngerepotin orang. Padahal anaknya sendiri pengen ngasih uang tiap bulan ke orangtua, Mbah Kakung nggak mau. Malah bilang kamu kan baru punya bayi, itu uangnya bisa dipake buat keperluan bayi. Ya kamu itu bayinya, Mbak.” Tutur Mama sambil masih menatap nanar tulisan di batu nisan itu. Sifat Mbah Kakung yang satu ini masih aku pegang teguh sampai sekarang. Aku tidak ingin merepotkan orang lain. Aku harus bisa berdiri di atas kakiku sendiri.
Matahari tepat berada di atas kepala kami. Beberapa pengunjung lain sudah mulai beranjak pergi meninggalkan pemakaman. Banyak yang tidak langsung pulang dan mengunjungi monumen yang menjulang di tengah-tengah kawasan pemakaman. Ada juga yang mulai ber-swafoto sambil mengelilingi batu nisan. Mulai terdengar kericuhan kecil untuk melihat hasil foto dan langsung minta dibagikan ke gawainya. Aku hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat fenomena itu sembari mengumpulkan buku surat yasin yang tertumpuk pada ujung makam. Papa bangkit dari duduknya, membawa botol berisi kopi hitam, dan pergi menuju parkiran mobil. Petugas makam yang sibuk mengumpulkan kursi dan ember sudah melirik-lirik ke arah kami yang nampak sudah siap pergi. Namun Mama tidak akan pernah siap pergi. Jika memungkinkan, pasti Mama ingin berlama-lama di makam Mbah Kakung. Mungkin mengenang masa-masa hidup Mama saat masih ada Mbah Kakung. Enaknya memiliki sosok bapak yang melindungi dan tidak pernah memaksa kehendaknya. Hangatnya sebuah keluarga yang dipimpin oleh seorang bapak yang dapat merangkul anak-anaknya. Untungnya Mama tidak terbiasa naik kendaraan umum dan kami sekeluarga hanya memiliki satu mobil. Kalau aku dan Papa ingin pulang, Mama terpaksa mengikuti kemauan kami. Aku merogoh uang dua puluh ribu dari dompet dan melambaikan tangan ke petugas makam itu. Mama masih saja meratapi makam Mbah Kakung. Tiap tahun, pasti dia mengambil tiga buah batu dari makam. Buat kenang-kenangan katanya. Tidak ada yang bisa menggantikan Mbah Kakung di hati Mama, bahkan Papa sekalipun.
“Pak, titip makam ya. Tolong dirawat.”
“Makasih ya, Mbak. Bapak kemana, Mbak?”
“Oh, udah duluan tadi. Nggak enak, kita parkir ngehalangin mobil orang. Takutnya yang punya mobil udah mau pulang, Pak.”
“Iya, Mbak kalau lebaran gini ramai betul. Kadang kami juga kewalahan bawain kursi sama air tiap kali ada yang berkunjung.”
“Makasih banyak ya, Pak. Saya sama Ibu pamit dulu. Ayo, Mah. Udah ditunggu Papa di mobil.”
Wangi khas pemakaman melambaikan tangannya dibalik punggung kami.
***
“Ayo-ayo sudah azan, nggak boleh minum lagi. Sudah niat puasa kan, Mbak?”
“Kata siapa?”
“Kata Mama Dede kemarin di TV. Ayo gelar sajadah. Terus panggil Papa tuh di kamar. Kita sholat sama-sama.”
Aku paling benci disuruh-suruh begini. Segala hal yang berkaitan dengan Papa pasti harus aku yang meminta. Bagai burung hantu, aku diminta mengantarkan pesan yang bisa Mama sampaikan sendiri. Aku paham perasaan Hermione saat menyampaikan pesan Harry ke Ron dan pesan Ron ke Harry saat mereka tidak mau berbicara satu sama lain pada film Harry Potter and the Goblet of Fire. “I’m not an owl!” Ingin aku teriak ala Hermione ke Mama, tetapi aku urungkan niat.
Memang bukan salah Mama karena Papa memang tidak pernah mendengarkan Mama. Papa tidak melakukan hal-hal yang Mama minta. Atau melakukan hal-hal yang mama minta beberapa jam kemudian. Bahkan beberapa hari kemudian! Aku tidak mengerti apa yang salah diantara mereka. Setelah aku balik dari perantauan selama 8 tahun, cara komunikasi mereka sama sekali tidak efektif. Mama senang sekali aku pulang karena aku bisa menjadi burung hantu untuk menjembatani komunikasi mereka yang sudah rusak parah. Awalnya aku senang-senang saja menjadi burung hantu, namun lama kelamaan hal ini sangat membosankan dan juga payah! Pernah suatu hari aku pergi seharian. Mama meneleponku berkali-kali dan memang aku tidak sempat mengangkatnya. Ketika telepon yang ke-13 kalinya aku angkat, Mama memintaku untuk menelepon Papa untuk mengganti galon air minum. Ya Tuhan! Padahal kedua orang itu sedang berada di atap yang sama.
Papa tidak banyak bercerita sehingga sekarang aku tidak begitu mengenal Papa. Aku ingat, sewaktu aku masih kecil, Papa teman yang mengasyikkan. Papa dan aku sama-sama senang bermain Play Station. Untuk ukuran orang dewasa, Papa termasuk jago bermain. Berbeda dengan Mama yang memilih permainan Land Before Time dimana dinosaurus berlari otomatis. Kita hanya perlu menekan tombol agar dinosaurus itu melompat atau menghindari rintangan ke kanan dan ke kiri. Aku dan Papa senang sekali bermain Crash Bandicoot N Sane Trilogy. Papa paling senang kalau Crash sudah dikejar-kejar bola atau beruang kutub raksasa. Aku ingat betul saat sedang ujian sekolah, aku bersibuk diri dengan buku pelajaran sedangkan Papa bermain Crash Bandicoot di ruang tamu. Saat itu aku ingin cepat-cepat lulus sekolah agar bisa bermain Crash Bandicoot sepuasnya. Sayangnya Play Station itu dijual saat aku baru masuk sekolah menengah pertama. Keceriaan Papa juga ikut raib, hanyut, terbawa Play Station kesayangan kami. Sejak saat itu, kami tidak pernah bermain bersama lagi. Aku sibuk dengan masa remajaku dan Papa sibuk mencari uang untuk memenuhi tagihan-tagihan bulanan kami. Seandainya aku bisa mengganti Play Station itu dengan benda lain sebagai wadah komunikasiku dengan Papa. Sayangnya aku tidak menggantinya sampai detik ini.
Aku membuka pintu kamar dan menemukan Papa sedang memainkan gawainya. Papa memang senang membaca cerita yang entah menceritakan kisah apa di website yang juga entah apa itu. Papa seperti punya dunianya sendiri jika sedang membaca cerita itu. Bukan hal yang mengejutkan bagiku menemukan Papa sedang tiduran telantang dan membaca sesuatu digawainya tanpa melihat ke arahku. Bau aneh lah yang mengejutkan penciumanku dan membuat sedikit mual. Apa aku kurang banyak menggunakan karbol saat mengepel semalam? Tetapi kamarku tidak berbau aneh begini. Cuping hidungku kembang kempis mencari asal muasal bau itu. Tak sempat menemukan sumber bau busuk itu, Mama sudah berteriak dari ruang tamu. Akhirnya aku dan Papa memenuhi panggilan sholat Mama yang mengalahi azan masjid. Namun aku tidak bisa berkonsentrasi sholat karena bau busuk itu seperti menetap di dalam hidungku. Kenapa ruang tamu menjadi bau busuk begini? Aku mengusap-ngusap hidung agar wangi mukenah dapat mengalahkan si bau busuk. Apa Mama tidak merasakan bau busuk ini? Untunglah sekarang sudah tinggal sesi berdoa. Aku berdoa agar aku tidak muntah dan membatalkan puasaku yang baru berjalan 10 menit. Mataku mulai berkunang-kunang dan kepalaku mulai pening. Aku menatap Papa yang menjadi imam dan duduk di depan aku dan Mama. Seperti ada yang aneh, tapi apa ya? Astaga! Papa masih memakai baju yang sama. Aku yakin sekali Papa hanya punya satu baju bertuliskan “Wonderful Indonesia” dengan corak hijau putih itu. Baju itu kini sudah lecek sana-sini dan bahkan warnanya sudah agak kekuningan pada bagian ketiak. Apakah Papa sudah mandi? Aku yakin sekali sumber bau busuk ini dari aroma tubuh Papa. Oh Tuhan, bagai mayat hidup!
“Disuruh ganti baju aja nggak mau, Mbak. Apalagi disuruh mandi.” Mama terkekeh-kekeh melihat aku menutup hidung saat Papa mendekat ke arah kami.
10 Mei 2020
Hujan turun, membanjiri lantai kamar
(Karya: Ayuwinati)