Aku Johan Coenraad van Hasselt. Kau bisa memanggilku Johan. Aku dilahirkan di Doesburg pada tanggal 26 Juni 1797. Hati dan jiwaku jatuh dalam pelukan alam sejak kecil, sehingga tak perlu berpikir dua kali saat de Natuurkundige Commissie1 menawariku sebuah petualangan di Jawa. Kata banyak rekan, Jawa merupakan potongan Nirwana yang sangat jauh dari Eropa. Suatu bagian dari Hindia Belanda. Berbekal api semangat yang berkobar dahsyat dalam dada, aku berlayar menuju surga dunia pada tanggal 11 Juli 1820 melalui Kepulauan Cocos, wilayah kekuasaan Australia paling luar yang terletak di Samudera Hindia. Tentunya, aku tak berkelana sendirian. Dia pun turut menemaniku. Dia, seorang naturalis dan zoologis berdarah Jerman.
Pada bulan Desember kami menginjakkan kaki di tanah surga bernama Jawa. Kedua mata ini menjadi saksi akan keindahannya. Ternyata, apa yang dibicarakan oleh bangsaku tentangnya memang benar. Sesungguhnya Jawa memang potongan taman Firdaus! Suasananya sangat jauh berbeda bila dibandingkan dengan tanah kelahiranku. Sejauh mata memandang, zamrud hijau menghiasi pertiwi. Di sini, di tanah Jawa, sebuah harapan membuncah dari relung hati terdalam. “Semoga perjalanan di bagian tropis ini dapat memberikan kami sumbangsih bagi ilmu pengetahuan”, kataku. Dia memandang lalu menepuk pundakku perlahan. Senyuman indah tersungging di bibirnya dan tanpa berkata-kata sepertinya ia mengamini doaku. Masih di bulan yang sama, kami berdua menjelajahi Bantam, Gunung Karang, dan Gunung Poelasari.
Kondisi fisikku melemah saat menapaki Gunung Poelasari. Mungkin karena gumpalan rasa letih yang terakumulasi sejak perjalanan laut. Rasa pening yang teramat sangat mulai menggerogoti isi kepala. Ribuan serangga dengan bokong yang menyala berterbangan di sekitar mata. Aku limbung! Raga ini tak kuat menopangku. Aku terjatuh. Kaki kiri terkilir dan celanaku berhiaskan lumpur. Dia dengan cekatan segera membantuku. Diraihnya tanganku dan dibantunya aku berdiri. Beberapa kuli pribumi mencibir dalam bahasa yang tak ku pahami. Tak lama berselang, rasa sebal ini pun terbayar kontan, saat ia berlari menghampiriku dengan senyuman terindah di wajah tampannya. “Johan, ikuti aku! Kemudian tutuplah kedua matamu”, katanya sembari menarik tanganku. Tentu saja aku mau mengikutimu! Aku tercengang saat membuka kelopak mata. Sebuah air terjun cantik berdiri kokoh di hadapanku. Airnya yang jernih menerjuni tebing tanpa ragu. Aneka tetumbuhan cantik menghiasi setiap jengkalnya. Mereka menjadi saksi atas kebahagiaan kami di hari itu. Tuhan…. terima kasih telah mengiringku ke dalam taman surgawi bersamanya.
Tujuh bulan setelah perjalanan di Karesidenan Bantam, de Natuurkundige Commissie kembali menugaskan kami ke Tanah Priangan. Kali ini Gunung Halimun-Salak hingga Pangrango-Gede di Buitenzorg lah yang menjadi sasarannya. Eksplorasi akan berjalan hingga awal Agustus 1821. Aku agak ragu saat itu. Rasa enggan menelusupi dada. Aku dihantui kecemasan. “Apa yang kau cemaskan, Johan? Ingat, tujuan kita melangkahkan kaki di tanah ini semata-mata untuk menuntaskan segala dahaga yang ada”, tuturnya. Tuhan.. bersama dia di sini membuatku tenang.
Perjalanan ternyata berlangsung sangat berat. Tekanan dari alam cukup membebani. Cuaca buruk dan medan terjang menemani setiap langkah kaki. Aku berkali-kali jatuh dan dia selalu ada di sisiku. Di suatu malam pada pertengahan bulan Juli, angin berceracau riuh. Mengerikan. Sebuah mimpi buruk di pegunungan Jawa. Kerangka kami dibuat bergemerutuk olehnya. Beberapa pribumi menawarkan secangkir air jahe hangat. Di dalam tenda berpenerangan rendah itu, jemarinya memeluk jemariku. “Terima kasih kau selalu menemani hingga detik ini di tanah yang asing bagiku”, ujarnya. Aku membuang muka, tak berani berlama-lama memandangnya. Air mata tak kuasa menahan lelehannya di pipi. Semoga kau diberkati Tuhan, aku mengucapkannya dalam kalbu. Hanya aku dan Tuhan yang tahu.
Ribuan tanya selalu bergema dalam hati dan belum kutemukan jawabnya. Mengapa dia menjadi teristimewa? Bahkan sejak pertama kami bertemu di Groningen. Setiap waktu bergulir, perasaan ini semakin menjadi. Laksana api yang membakar perkamen. Melihat bayangnya saja pun mampu membuat dada ini semakin bergejolak. Aku suka sekali senyumnya. Juga tatapannya untukku. Tatapan teduh yang membuat diri ini seperti butiran salju di akhir musim dingin. Andai aku dapat mengatakannya, aku menikmati setiap detik bersamanmu. Waktu di saat kita bekerja dan berdiskusi bersama. Kau lebih dari sekedar seorang teman. Aku akan selalu ada untukmu. Jiwa dan ragaku tak mendustainya. Ab imo pectore2.
Di akhir bulan Juli, ia jatuh pingsan saat mengukur seekor katak yang baru kami dapatkan dari tepian sungai. Tubuh tegapnya kini seperti menara babel yang diruntuhkan Tuhan. Ia tak sadarkan diri selama beberapa malam. Ternyata selama ini dia sakit! Kecemasanku selama ini terbukti. Aku kecewa. Marah sekali. Ia selalu berusaha terlihat kuat di depanku. Badannya panas tinggi seperti sahara. Wajahnya tampannya kian meredup. Lingkaran hitam bertengger di matanya. Kegiatan ilmiah aku tinggal deminya. Kubaringkan tubuh ini di sampingnya. Tak beranjak sedikit pun. Berharap Tuhan memberikan keajaibannya di tengah hutan ini. Keesokan malam, ia tersadar dari mimpi panjangnya. Aku sangat bahagia malam itu. Rupanya Tuhan masih mendengar doa-doa yang kupanjatkan. Aku menangis melihatnya terbangun. “Johan… “, kata pertama yang terlontar dari mulutnya. Aku di sini, sayang! Selalu di sisimu. Segera kuambil air dan memanggil seorang pribumi di luar tenda untuk membawakan semangkuk bubur yang masih panas. “Kau makan dulu. Biar aku suapi”, ujarku sembari menyendok sesuap bubur dan meniupinya. Ia membuka mulutnya perlahan, dan mengusap pipiku. Malam itu, aku memeluknya erat. Erat sekali. Hingga sang mentari menyinari rimba keesokan paginya.
Sekian lama ku mengenalnya, dia selalu berusaha menjagaku. Meski, aku lebih tua 3 bulan darinya. Ia anak kedua dari keluarganya, sedang aku sendiri anak kelima dari orangtuaku. Dia adalah kakak, seorang yang spesial, sekaligus rekan kerja untukku. Dua hari setelah ia siuman dan tubuhnya membaik, kami memutuskan untuk segera keluar dari rimbunan pepohonan. “Kali ini ijnkanlah aku menjagamu”, kataku. Pagi itu aku menggendongnya di tengah kabut. Menuruni Gunung. Aku bisa merasakan setetes air mata jatuh membasahi pundak. Illis quos amo deserviam3.
***
Perkenalkan, aku Heinrich Kuhl. Pemuda berdarah Hanau, Hessen-Jerman, yang acap kali terlihat galak. Oh ya, kau dapat memanggilku Heinrich. Hari itu, 11 Juli 1820, untuk pertama kalinya aku berlayar menuju Jawa, sebuah kebun Hesperides di Hindia Belanda, atas perintah de Natuurkundige Commissie. Aku menempuh perjalanan jauh bersamanya. Seorang zoologis kelahiran Belanda. Aku ingat sekali wajahnya, saat ia pertama kali mendaratkan diri di bumi Hindia Belanda. Matanya berbinar penuh pengharapan. Aku mendengar ia menggumamkan sebait doa, lalu aku mengamininya dalam diam.
Aku bertemu dengannya di Groningen untuk pertama kali. Dia seorang pemuda yang sangat berdedikasi untuk ilmu alam. Sebenarnya banyak perbedaan di antara kami. Aku seorang pria yan selalu terlihat rapi, sedangkan dia bergaya santai sekaligus paling bergaya. Sejak awal berjabat tangan dengannya aku menemukan sebuah kecocokan. Seperti terdengar bunyi “klik” jauh di dalam relung hati di sana. Sejak itu pula kami sering membunuh waktu bersama-sama. Baik di dalam maupun di luar kegiatan ilmiah. Bersama dengannya, kami kritisi Linnaeus4. Kami pun berguru dari satu orang yang sama, Theodorus van Swinderen5. Aku dan dirinya dinobatkan sebagai dua anggota termuda pertama di de Natuurkundige Commissie.
Aku tak berpikir dua kali saat mereka menugaskan kami di Jawa. Aku bahagia dapat menjelajahi alam Jawa bersamanya. Rona wajahnya menunjukkan ketenangan saat langkah kakiku menemani perjalanannya di tengah belantara yang basah. Saat tanganku dengan cekatan menggapai tubuhnya di dasar hutan. Masih dapat digambar ulang secara jelas, saat sebuah air terjun di Gunung Poelasari menjadi saksi bisu atas hubungan kami. Potongan-potongan adegan lalu juga terlintas kembali di benakku. Waktu di mana kami mencatat pelbagai jenis herpetofauna dan ikan. Saat memberi nama bagi anak-anak kami. “Megophrys monticola tentu nama yang cantik baginya, Heinrich!”, ujarnya dengan penuh bersemangat.
Sedikit kebimbangan menghantuiku saat mereka memberikan tugas kembali selama bulan Juli hingga Agustus 1821 di beberapa gemunung di Buitenzorg. Tak hanya aku, wajahnya pun terlihat cemas. Aku menanyakan sebab kecemasannya. “Aku mencemaskanmu, Heinrich. Sejak tujuh bulan ini bahkan kau belum sempat beristirahat. Wajahmu pun kini sepasi rembulan”, jawabnya. Ah.. kau tak perlu mencemaskannya. Bersamamu tak akan ada aral melintang di depan. Percayalah!
Malam itu, suatu malam di tengah bulan Juli, angin kencang menghembuskan jiwanya di sisi pegunungan. Sangat kencang. Pepohonan pun mampu tercerabut dari tanah. Tubuhku menggigil dan mulai letih. Lagi-lagi rasa nyeri memancar dari bagian ulu hatiku. Mungkin karena belum banyak beristirahat. Di dalam tenda yang hangat aku mendekatinya. Ku pegang erat jemarinya. Kau yang teristimewa untukku. Aku akan selalu ada untuk menjagamu. Seperti Gede-Pangrango atau Halimun-Salak, kita selalu bersama. Semoga kau tahu itu.
Menjelang hari-hari terakhir di tengah belantara raya, aku semakin tak kuasa menahan rasa sakit di ulu hati. Mual sekali. Dalam hitungan detik, aku terjatuh. Seekor spesimen yang kupegang terlepas dan berhasil meloloskan diri. “Heinrich!”, ia meneriakkan namaku. Selanjutnya warna gelap menguasai diri. Beberapa malam sesudahnya aku terjaga dalam demam. Peluh dingin berlarian di sekujur tubuh. Saat membuka mata, ku dapati ia di sisiku. “Puji Tuhan.. kau sadar, Heinrich!”, ia menatapku dengan sangat cemas, meski amarah menyemburat dari wajahnya. Kemudian ia panggil seorang pribumi untuk membawakan semangkuk bubur yang baru matang. Dengan cekatan dalam penuh kehati-hatian, ia suapi aku. “Buka mulutmu”, ujarnya dengan lembut. Ia tidak berubah. Masih sama seperti dulu saat aku sakit di Jerman. Aku selalu tak ingin membuatnya cemas, meski ku tahu keputusanku untuk tetap bisu dalam sakit di tengah gelap belantara membuatnya terluka. Malam itu, dia peluk tubuhku erat. Seperti akar yang mencengkeram tanah. Bibir tipisnya mendarat di keningku.
Dua hari setelahnya, setelah dirasa tubuhku mulai membaik, kami memutuskan untuk segera menuruni gunung. Sayangnya.. sang alam masih menyombongkan diri. Kabut tebal menyelimuti bumi. Ia yang sebelumnya acap terjatuh di hutan Jawa, kini melangkahkan kaki dengan aku di punggungnya. Aku bangga padamu.
***
Halilintar besar menyambarku siang itu di bulan September. Aku terpekik. Seperti ada yang mengganjal kerongkonganku. Tak dapat berkata-kata, ibarat seekor ikan yang kehilangan airnya. Penopang hidupnya. Aku menangis menjadi-jadi. Nafasnya semakin memendek. Aku tak tahan melihat raganya berjuang melawan maut. Semua orang di ruangan itu tertunduk. Aku hanya dapat memeluk tubuhnya. Tuhan, ambil saja aku! Nafasnya tersengal. Di ujung tanduk. Dia menatapku dan air mata meleleh di ujung matanya. Tangannya memegang erat. “Maafkan aku..”, hanya itu yang ia ucapkan. Lalu tertidur lelap. Seperti seorang bayi yang tidur nyenyak di pangkuan Ibunda.
***
Johan.. maafkan aku. Masih ingatkah kau dengan sebuah pepatah latin kuno, Etiam in morte, superest amor? Ya.. Dalam kematian, cinta masih bertahan.. Aku menyayangimu.
Buitenzorg, Awal September 1821
Heinrich-mu
***
Kuhl meninggal pada tanggal 16 September 1821 akibat infeksi hati. Dua tahun kemudian, van Hasselt menyusulnya pada bulan September 1823 karena serangan disentri. Keduanya dipertemukan kembali dalam satu liang lahat yang sama. Makam mereka masih berdiri kokoh hingga saat ini di Kebun Raya Bogor.
Nama keduanya diabadikan sebagai nama penunjuk jenis untuk berbagai macam hewan dan tumbuhan, termasuk anggrek Dendrobium hasseltii dan Dendrobium kuhlii, yang tumbuh bersama dalam hutan lumut di Gunung Gede. Kedua jenis tersebut dianggap dapat mengilustrasikan kedekatan di antara mereka. Dr. J.J. Smith6 bahkan memadukan nama keduanya sebagai sebuah marga anggrek Jawa, yaitu Kuhlhasseltia.


Bogor, 29 Mei 2016
A. Surya Dwipa Irsyam
___________________________________________________________________________
Catatan:
*) Una in perpetuum merupakan sebuah ungkapan dalam bahasa latin yang berarti “forever together”. Ungkapan kuna tersebut menggambarkan kedekatan antara van Hasselt dan Kuhl yang tak terpisahkan oleh maut. Bersama selamanya.
1) de Natuurkundige Commissie: suatu komisi bentukan Pemerintah Hindia Belanda yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan alam.
2) Ab imo pectore: dari hati yang terdalam.
3) Illis quos amo deserviam: For those I love I will sacrifice.
4) Linnaeus (Carolus Linnaeus atau Carl von Linné; 1739-1778): seorang taksonomis berkebangsaan Swedia yang mencetuskan dasar-dasar tata nama biologi.
5) Theodorus van Swinderen (1784-1851): Seorang Guru Besar dalam bidang sejarah alam di Universitas Groningen, Jerman.
6) J.J. Smith (1883-1947): Seorang taksonomis berdarah Belanda yang mempelajari pelbagai jenis Anggrek (Orchidaceae) di kawasan Hindia-Belanda.
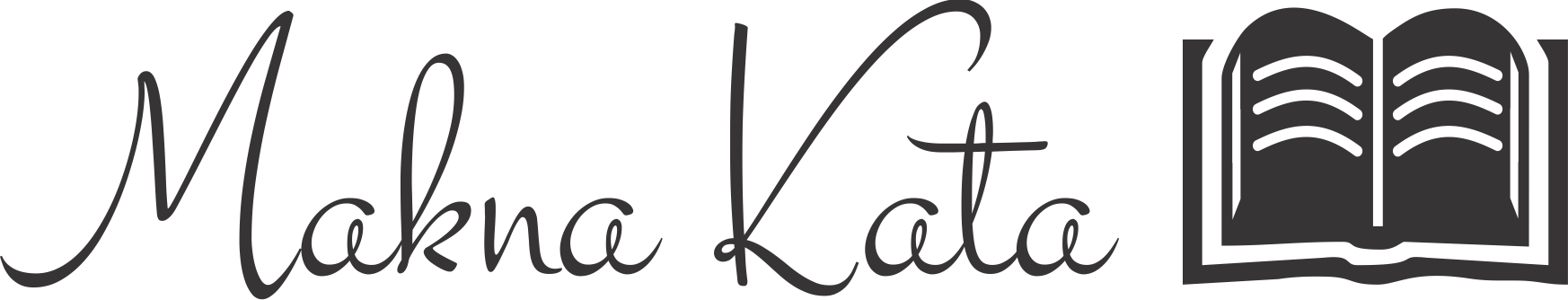
Ajib Mas Surya..ini adalah karya terbaik Anda sejauh ini. Ceritanya cukup mengalir, penuh emosi, dan sarat
akan sejarah kolonil Belanda serta tak luput dgn bidang keilmuan. Ramuan yg pas. Pastinya butuh riset panjang ya untuk menulis karya ini. Congratz 🙂
hatur nuhun mbak. Berkat maknakata, gairah menulis saya bangkit kembali.
kece parah! lo selalu bisa menyampaikan sesuatu yg ilmiah lewat cerita yang menarik dan mengalir. inget cerita penyihir zaman medieval kak? yg pernah kakak cerita pas praktikum STB ttg Solanaceae , itu seru banget kak. bikin tulisan ttg itu keren kayaknya.
kece parah! lo selalu bisa menyampaikan sesuatu yg ilmiah lewat cerita yang menarik dan mengalir. inget cerita penyihir zaman medieval kak? yg pernah kakak cerita pas praktikum STB ttg Solanaceae , itu seru banget kak. bikin tulisan ttg itu keren kayaknya.