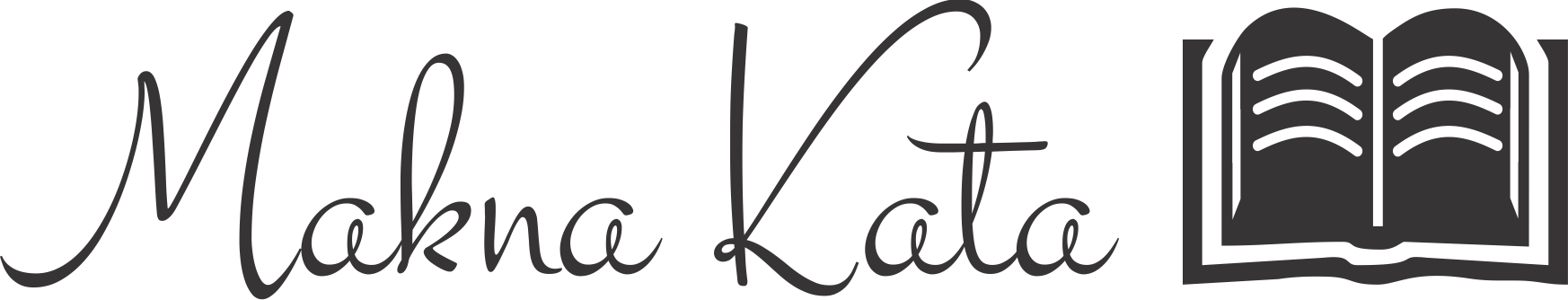Hidup, sebuah kata yang penuh glora. Manusia hidup di dalam kehidupan. Darah yang mengalir deras membuat rona merah pada wajah. Nafas yang terengah-engah saat bercinta. Suara riuh renyah saat menyantap roti panggang di pagi hari. Semuanya tenggelam dalam kata “hidup” bersama dengan teka-tekinya. Manusia bisa menulis jurnal tentang masa lalu, apa yang mereka lakukan pada hari-hari tertentu. Namun, hanya rencana yang dapat ditorehkan pada jurnal masa depan yang masih abu-abu seperti awan tak menentu untuk menitikkan air hujan atau hanya gerimis yang mengundang rindu. Rencana ini perlu dirancang sebaik-baiknya, terkadang tidak cuma satu. Kalau-kalau rencana gagal dilaksanakan, masih ada secercah harapan untuk melakukan rencana berikutnya. Ini demi melanjutkan hidup. Rencana menuntut kita untuk memilih sekian banyak strategi. Memilih merupakan sebuah tindakan yang penuh resiko. Jika pilihan sudah jatuh pada suatu hal, maka akan ada konsekuensi yang membuntuti bagai anjing budug kelaparan. Perlu waktu untuk memilih dan memang tidak sebentar atau janganlah terburu-buru, apalagi jika pilihan itu akan menghabiskan banyak energi yang kita miliki. Seperti halnya memilih sebuah rumah. Rumah seperti apa yang dapat menaungi dengan baik? Sebenarnya kita tidak akan pernah tahu sampai kita menempati rumah itu. Kita hanya bisa menebak-nebak, mempertimbangkan berbagai hal, dan belajar dari orang-orang yang sudah memiliki rumah. Rumah beratapkan seng atau genteng sama-sama melindungi diri dari hujan. Namun, dibalik suatu fungsi, terdapat konsep nilai. Manusia sibuk menilai benda-benda seakan-akan benda-benda tidak berhak menilai dirinya sendiri. Rumah beratapkan seng dinilai lebih rendah dibandingkan yang beratapkan genteng. Genteng menjadi sebuah komoditi yang lebih modern, mahal, dan menjanjikan. Segala yang kebarat-baratan dianggap bernilai lebih baik. Aku tak berfikiran begitu, walaupun genteng memang membuat penampilanku lebih menarik.
Aku dibangun pada tahun 1990 di daerah Jakarta Selatan, setidaknya dulu namanya Jakarta Selatan. Sekiranya bersaudara, aku punya banyak sekali saudara kembar. Mungkin ada 100 saudara kembarku di sini, namun aku tidak bisa memastikan karena aku tertanam kuat pada tanah bekas rawa-rawa ini. Itu sayup-sayup yang aku dengar jika ada agen properti mempromosikan diriku. Dia nampak berkeringat pada hari yang tidak terlalu panas. Mungkin karena pakaian rapihnya yang berlapis-lapis itu. Berkali-kali dalam bulan ini dia berdiri bersama orang asing yang silih berganti. Kali ini, orang asing itu tampak pura-pura mendengarkan, sambil melihat dengan tajam ke arahku. Sekali-kali melemparkan pandangan ke arah saudara-saudara kembarku yang sudah dihuni oleh orang asing lainnya. Wajahnya menunjukkan rasa penasaran mengapa hanya aku yang belum dihuni. Sekali-kali dapat kutangkap dari matanya yang memancarkan ketakutan akan hal-hal gaib. Yang benar saja! Ingin aku mengumpat, tapi aku tak tega dengan kucing yang sedang tertidur di sela-sela atap. Nanti dia terbangun dan mencari rumah lain. Wahai orang asing, percaya lah, membeli rumah itu seperti mencari jodoh. Aku belum menemukan jodohku saja, biar waktu yang menjawab. Tiba-tiba ketengangan di wajahnya mengendur ketika ada orang asing lain menghampiri dan merangkulnya dari belakang. Orang asing ini lebih ramah, setidaknya dia selalu tersenyum saat melihat ke arahku. Aku suka dengan orang asing yang ini. Agen properti mulai menyilahkan mereka masuk, menelusuri isi perutku, benarkah isi perut? Terkadang aku merasa geli ketika mereka mengetuk-ngetuk dinding dan kusen. Hatiku berdebar-debar saat mereka membuka satu persatu pintu ruangan. Aku merasakan angin segar saat mereka membuka jendela yang menghadap ruang belakang. Aku serasa dilahirkan kembali. Sebelumnya, tidak ada orang asing yang berlama-lama di dalam diriku. Sudah sekitar 45 menit mereka di dalam, melihat-lihat, mengecek semua sudutku dengan teliti. Oh Tuhan! Jika aku punya tangan, aku ingin menutup mulutku yang sudah berteriak “Oh Tuhan!”. Aku benar-benar terkejut saat agen properti bersalaman dengan orang asing nan ramah itu. Mereka kah jodohku? Ingin aku berlari-larian dan melompat-lompat kegirangan bagai anak kecil yang pertama kali melihat padang rumput.
Aku sedikit merasa hangat di dalam perutku. Aku rasai betul hangat ini, membangunkanku pada hari minggu pagi malas berlangit mendung. Namun ini hangat yang berbeda dari biasanya. Bukan hangat yang biasa terasa setiap pagi, siang, dan malam di pojok tubuhku yang mereka sebut dapur. Hangat ini kecil mungil namun memancarkan cahaya harapan baru, seperti gelak tawa orang asing kecil yang baru muncul lima tahun yang lalu. Mereka bertiga berkumpul di ruang makan mengitari nyala api-api kecil di atas sebuah kue tart. Orang asing kecil itu seperti bersiap-siap meniup api-api kecil. Oh api-api kecil yang malang, akhirnya mereka padam. Perutku dihiasi asap tipis yang perlahan-lahan membumbung ke langit-langit dan tubuhku berangsur-angsur kembali mendingin. Aku perhatikan betul mereka yang tampak tidak bosan dengan ritual ini. Mereka saling peluk dan cium serta memanjatkan doa yang terbaik. Setiap tahun mereka selalu melakukan ritual ini, sederhana namun membuat diri ini menitikkan air mata haru. Aku lah saksi bisu apakah doa-doa itu akan dikabulkan kelak. Setiap doa diiringi harap-harap yang bertambah setiap tahunnya. Setidaknya bagi orang asing kecil. Aku mendengar sayup-sayup harapannya tahun ini. Dia ingin bisa menjadi peringkat pertama di kelasnya. Aku hanya mengucap “aamiin”, walaupun aku tidak tahu pasti harapan macam apa itu. Lima tahun sudah mereka aku naungi. Tubuhku masih kokoh dan tak kubiarkan serangga-serangga kecil mengganggu tidur mereka. Kerja kerasku selama musim hujan terbayarkan dengan seulas senyum saat mereka tidur berhimpitan di dalam selimut. Begini ya rasanya menjadi sebuah rumah, aku merasa diberkati. Walaupun terkadang aku terkejut ketika pintu kamar dibanting. Aku membelalakkan mata ketika suara teriakkan membahana dalam tubuhku. Piring-piring porselen yang dibanting ke lantai, membuat lantaiku sedikit retak. Setiap kali hal-hal ini menerorku, aku melihat orang asing kecil hanya duduk di teras. Kadang sembari memainkan mainannya dan berpura-pura acuh tak acuh pada porselen dan makian yang berjatuhan ke lantai. Terkadang aku merasa iba dan ingin memeluk orang asing kecil. Aku menerka-nerka apa yang ada dipikirannya. Selalu aku panggil kucing agar lewat depan teras sehingga dia bisa terhibur. Ternyata tidak hanya terhibur, namun dia jatuh cinta dengan kucing, melebihi cintanya kepada orang asing yang saling tunjuk menunjuk di dalam tubuhku.
Sepertinya orang asing kecil ini benar-benar menganggap kucing seperti anaknya sendiri. Begitulah setidaknya yang aku lihat 18 tahun kemudian. Tentunya bukan kucing yang aku undang untuk menghiburnya dulu. Ini kucing yang aku minta datang untuk menjadi penengah mereka. Ya orang-orang asing ini semakin berlipat-lipat, muka dan emosinya. Tidak terjalin komunikasi yang baik diantara mereka. Jika tak ada perlu mereka saling diam. Jika ada perlu baru lah bicara. Bicara sedikit saja bisa mengundang makian dan tangisan. Maka aku minta kucing itu datang agar suasana tidak selalu tegang, kira-kira 8 tahun yang lalu. Namun semua makhluk hidup harus pergi dan menjadi tidak bernyawa lagi, tidak terkecuali kucing ini. Kucing ini dimakamkan di pekarangan depan di dekat kolam ikan. Ada sebidang tanah yang dulu ditumbuhi pohon pepaya. Orang asing kecil yang sudah tumbuh dewasa itu meratapi kuburan kucing dan menangis terisak-isak. Kira-kira, orang asing kecil sebelumnya pergi selama dua minggu, dan kucing ini mati ketika itu. Tak heran mengapa dia sampai sesak nafas, kata-kata perpisahan terakhir pun tidak sempat diucapkan. Kucing yang sudah menemani keluarga itu selama 8 tahun, yang selalu menjadi pelarian dari pertengkaran tiada henti, sudah tidak ada. Apa yang sebenarnya ditangisi orang asing kecil? Sudah tahu lah aku tugasku kedepannya, memanggil kucing lain. Aku sudah menua, gentengku sudah bergeser, langit-langitku sudah berjuntai, dan sering mengalirkan air hujan. Kusen-kusenku sudah tidak sekokoh dulu lagi, dan membebaskan serangga-serangga keluar masuk. Dalam kerentaan ini, tidak ingin aku melihat mereka menghabiskan sisa hidup hanya berkelahi saja. Biarlah aku tidak dipugar atau direnovasi menjadi minimalis seperti saudara-saudaraku. Namun, aku tidak ingin diriku semakin hancur setiap pintu-pintu dibanting dan piring porselen berterbangan. Atau tembok yang retak setiap kali dipukul. Beginikah memang menaungi sebuah keluarga kecil? Aku kira, setiap tahun, setiap mereka meniup api-api kecil itu harapan akan semakin bertambah. Namun, setiap api-api kecil itu dipadamkan, harapan mereka semakin sedikit dan sampai pada titik tidak ada harapan sama sekali. Hidup bagai mayat, tidak ada perasaan, pandangan mata kosong, hidup sekedar hidup. Tidak ada kehangatan lagi selain api dari dapur. Tidak ada glora lagi pada mereka. Aku harus memanggil berapa ekor kucing?
Saudaraku pernah berbisik bahwa rumah bukanlah yang seperti kami-kami saja. Aku kira dia hanya bercanda, namun raut wajahnya tak berkata demikian. Ada pula rumah ibadah, dimana orang akan memanjatkan puji-pujian terhadap penciptanya. Rumah ini terbuka untuk orang asing mana pun, bahkan hanya untuk menumpang ke kamar kecil gratis. Tak terbayang olehku betapa kotornya rumah ibadah itu diinjak-injak ribuan orang. Namun saudaraku menjelaskan ada orang asing yang mengurus kebersihan dan perawatannya. Lain persoalan dengan rumah sakit, memang manusia makhluk malang. Sakit pun mereka harus tinggal beberapa malam di rumah itu. Kelak bisa sembuh, bisa juga meninggal dan tidak kembali lagi. Dengan polos aku bertanya, kelak kemana jika tidak kembali lagi? Itu lah rumah peristirahatan terakhir. Hanya berupa gundukan tanah, bila kaya raya boleh dihias marmer setahun kemudian. Tanpa daun pintu dan jendela, tanpa kusen dan dinding. Tanpa atap yang melindungi dari panasnya sinar matahari! Mengapa pula manusia memilih tempat peristirahatan terakhir begitu sulit? Begitu tidak nyaman nampaknya untuk menjadi rumah terakhir. Saudaraku terdiam beberapa saat, membuatku ingin mencubitnya. Apa ada lagi rumah lain? Mengapa kau terdiam? Rumah sakit jiwa, bisiknya. Jiwa? Bagaimana jiwa yang sakit? Bisakah disembuhkan? Saudaraku termenung dan kembali fokus pada orang asing dalam naungannya. Aku hanya tertegun, waktu itu. Tak sengaja mata ini terpaut pada loreng-loreng dibalik hijau daun. Aku bertanya pada seekor kucing garong di balik semak-semak. Betul rupanya, dia menyaksikan sendiri. Tidak pernah dilihatnya tingkah-tingkah orang-orang itu di sekitar sini. Jiwa mereka seperti dilahap habis, tidak bersisa. Aku hanya melongo bodoh, tidak dapat gambaran. Kucing garong kembali mendengkur.
Kini aku sangat mengerti ucapan kucing garong itu. Pasti dia akan berguling-guling di jalanan sambil menunjukkan perutnya padaku. Dia akan mengeong dan berkata “sedih sekali kau harus mendapatkan jiwa-jiwa itu dilahap zaman!” Hari ini dimulai ketika orang asing ramah tidak pernah keluar lagi. Tak lagi dia pergi dengan pakaian rapih dan mengendarai mobil dua pintu itu. Kebanyakan hari dihabiskannya dengan tidur dan menghisap berbatang-batang tembakau. Batang tembakau itu bagaikan sesajen yang serta merta harus tersedia di meja beserta kopi hitam pekat tanpa gula. Jika sesajen tidak ada, tidur saja kerjaannya. Tak ada nafsunya untuk makan, apalagi mencium dan memeluk dua orang asing lain. Apalagi mengurus diriku! Tak dibetulkannya pintu-pintu yang rusak. Tak dihiraukannya langit-langit yang bolong. Cat-cat mengelupas tidak dia sadari. Hati teriris perlahan-lahan rasanya, jika mengingat kembali hari pertama dia memilihku. Kini orang asing ramah, yang tidak lagi ramah, menghempaskanku. Tidak, dia tidak pergi, tapi dia tidak lagi peduli. Tak berhenti disitu penderitaanku. Orang asing satunya tak bisa tak merepet. Pagi, siang, dan malam kupingku panas dengan keluh dan kesahnya. Sekali-kali dia membersihkan tubuhku, tanpa nurani. Daki-dakiku masih banyak bersisa di sudut ruangan. Sarang laba-laba membentang di sana sini. Debu bukan lagi abu-abu, tak tahu lagi aku mendeskripsikannya. Sumpah serapah sudah seperti rapalan doa. Terngiang-ngiang dipikiranku, menjadikan diri ini tidak bisa berkonsentrasi. Penderitaanku masih juga berlanjut. Orang asing kecil, yang sudah tidak kecil lagi itu, seperti pohon tumbang. Tak ada lagi pada dirinya kepercayaan. Dirundung keraguan, kekalutan, tanpa masa depan. Sesekali dia pernah meringkuk di atas sofa, menangis. Beberapa menit kemudian tertawa terbahak-bahak. Seringkali dia hanya menangis, tidak tertawa lagi. Rambutnya tidak lagi dipangkasnya, menyapu lantai setiap dia berjalan gontai. Jatuh, rontok, rambut yang dulu ikal dan lebat itu mengotori diriku. Tidak lagi kebunku diurusnya. Malah sibuk menggali tanah dengan tangan, dan mengubur semua foto-foto lawas mereka. Aku merasa tak pernah lengah mengurus mereka. Bagaimana aku bisa luput saat jiwa mereka dilahap?
“Aku ingin tidur, hanya ingin tidur. Dengan tidur, aku bisa hidup dalam mimpi-mimpi yang indah. Jika harus terbangun, aku hanya ingin syarafku rileks bersama tembakau.”
“Aku tak punya teman bicara. Mereka tampak tidak ingin berbagi cerita padaku. Aku tak bisa memendam kesulitan ini di dalam hati, aku bisa sakit. Aku harus bicara.”
“Aku tidak tumbuh dengan kasih sayang. Lelah harus selalu berpura-pura punya belas kasih. Pohon pun bisa tumbang, begitu juga segala kemanusiaanku.”
Satu per satu malaikat maut mencatat serpihan jiwa yang tersisa.
Tangerang Selatan, 6 Juni 2020
Menyampaikan isi hati sebuah rumah
Karya: Ayuwinati