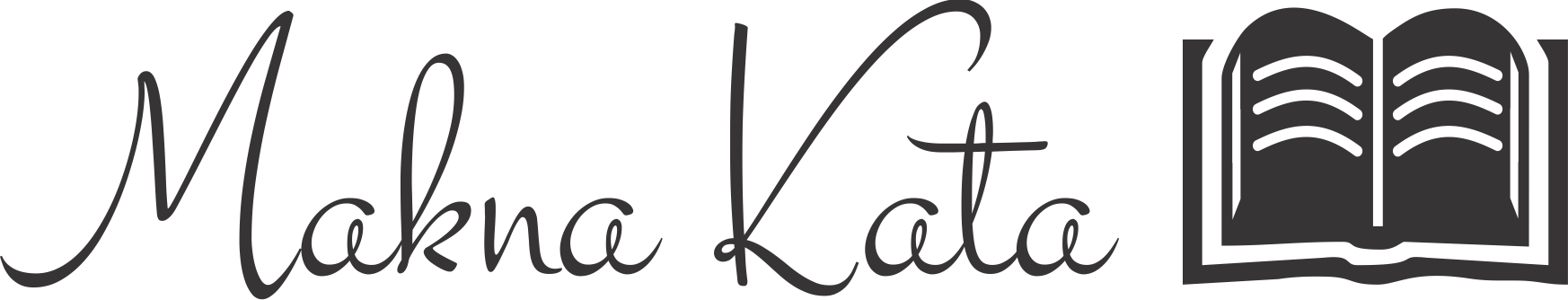Kabut masih menyelimuti kota ini, mengambang bagi kepala susu di dalam gelas sarapan pagimu. Kota kecil, awal segala kemungkinanku. Mungkin pula kemungkinanmu. Atau malah kemungkinan kita? Aku menghela nafas, asap putih menyelinap keluar dari mulutku. Menyelip cepat kenangan akan kamu. Kita dalam kota dan mereka.
Aku dulu tak peduli dengan apapun, aku hanya butuh tempat aman, jauh dari rumah. Rumah yang hanya nama tanpa ketenangan dan kebahagiaan. Tapi aku meninggalkan jantungku di rumah. Ia ibuku, berjuang sendiri dan aku bersembunyi di sini. Monster dirumahku, dalam wujud bapak tiriku, yang menyulut bara ini dan dengan setia menyediakan oksigen untuk menjaganya tetap menyala. Oksigen berupa tamparan, pukulan, bentakan bahkan ancaman penghilangan nyawa. Oksigen itu akhirnya berhasil mencapai titik sadarku, mengerogotiku. Aku dan otakku. Aku dan ragaku. Aku jadi tak percaya siapapun untuk menjagaku, Tuhan pun hanya formalitas. Bagaimana akau harus percaya, tak ada secuilpun asa yang bisa kujadikan pegangan. Tuhan hanya melulu mengisi hariku dengan teror satu ke lainnya. Rasa malu satu ke lainnya. Kesadaranku dalam hari hanya menuntutku segara pergi. Segera lari! Aku harus hidup dan aku harus selamat. Aku mudah tersulut, emosi mengelegak dan membesar sekali tersulut bagaikan api. Aku menjaga diriku dengan amarahku. Aku tak mau ada orang menyakitiku. Kalau perlu kusakiti dulu mereka, semacam peringatan untuk tak menyentuhku. Bara kemarahanku tak mungkin padam. Tapi kota ini, di mana aku sekarang menyusurinya kembali, berhasil menyusutkan baraku, bahkan mungkin memadamkannya. Kota yang menerimaku tapi menuntutku belajar untuk mengatur diriku. Renjanaku yang pertama.
Kamu, aku tak tau alasanmu kemari. Kau bilang sanakmu yang menyuruhmu datang kemari menemani sepupumu. Mungkin kau awalnya tak rela, karena kau ingin tetap di ibu kotamu yang angkuh. Siapa tahu? Tapi tenanglah, mungkin sudah ratusan orang yang mirip denganmu. Tak terlalu istimewa, toh kau tak pergi berlari kemari. Kita, tak sengaja bertemu. Atau sengajakah? Aku senang sekali melihat pertandingan futsal, aku memang senang olah raga dan selalu antusias bahkan saat duduk di tepian lapangan dan menontonnya. Kamu hari itu bertanding, biasalah aku memang ribut, menyemangati semua orang bahkan yang hanya kutahu nama tanpa identitas lainnya. Kamu bermain bagus sekali. Aku suka melihatmu, liukan kakimu saat menggiring dan mengoper bola siang itu. Kita, berlanjut dengan perkenalan saat acara refleksi bersama. Kamu yang tak paham, menuliskan kesan tentang acara padahal yang kuminta kesanmu tentang aku, temanmu. Aku terbahak saat membacanya, kamu tersipu malu karena salah mengartikannya. Kita, sampai sepupumu mengenalkan kita berdua. Lantas kita merajut sendiri pertemuan selanjutnya. Senyum, semangat, sapaan, awalnya kita malu menukarnya. Entah apa yang kita pikirkan saat itu sampai kau putuskan mengatakannya padaku. Tentu saja aku iyakan, walau tak sepenuhnya puas dengan caramu. Tapi cara hanyalah bentuk, perasaan sesungguhnya tak ada bentuknya bukan? Perasaan itu cair, cinta harus dibiarkan mengalir. Sampai tiba saatnya, dua tahun kurang bersama kita harus terpisah kota. Inilah janjiku, dulu saat ditanya temanku aku jawab kita akan berakhir saat perpisahan. Aku yakin, dan diam-diam tanpa mengatakannya padaku, kamu pun juga. Kamu tak bakalan bisa menjaga aku tanpa lindungan kota ini. Aku pun harus tetap menyingkir dari rumahku, rumah bermonsterku. Tapi entah doa siapa, atau Tuhan ingin kita belajar. Monster itu pergi dari rumahku. Lenyap! Benar-benar mujizat! Jelas keadaan ini meringankan perasaanku sehingga aku mulai yakin, mungkin kau boleh terus bersamaku dan belajar menjagaku. Kamu, renjanaku yang kedua.
Kota ini, tak semua menyimpan keindahan. Renjanaku tak melulu manis. Kesesakan dan kepahitan. Kalau kamu tahu, tak semua aku kisahkan padamu. Sudut-sudut tergelapku. Kusimpan bagai baju usang dalam lemari berbau apak. Mereka yang menempaku, dengan kata dan diamnya. Tajam dan menyesakkan bagai pahat pematung perkasa menguliti dan mebentuk kayunya. Butir air mata pun aku tahu rasanya, menahan tangis sampai darah terkecap di rongga mulut pun aku alami. Tapi apa hidup patut dirayakan kalau tanpa kepahitan. Pernah aku mencoba bicara pada mereka, berusaha membagi sesakku. Tapi aku terlalu sombong, aku mau mereka duluan yang bercerita. Aku ingin menjadi pelidung mereka. Aku tak mau rapuh di depan mereka. Sampai aku tahu rasanya aku telah kehilangan teman. Tapi mereka ternyata bukan temanku, mereka adalah keluargaku, di mana tak ada keluarga yang tinggal diam dengan nestapa anggotanya. Banyak dari mereka merasakan hal sepertiku. Bersama mereka aku belajar membuka diri. Bersama mereka, aku saling menguatkan, membalut luka, meyakinkan. Seperti obat, pahit tapi menyembuhkan. Mereka, renjana ketigaku.
Kita, aku dan kamu tanpa mereka, setelah perpisahan keadaan kita makin berat. Apalagi kamu sangat sibuk dan aku sering kali tak mau mengerti. Pertengkaran tak terelakkan, sampai kita sepakat untuk mengambil jarak, menambah rentang geografis dengan rasa. Aku tak tahan, kurasa begitu juga kau. Setiap pertengkaran ternyata membuihkan sekelumit pengganggu. Pengganggu mewujud keraguan, semakin lama aku semakin tak paham kamu, karena aku juga semakin kehilangan diriku. Mereka, keluargaku di kota itu, pun semakin sibuk dengan kegiatannya sendiri. Meninggalkanku yang semakin sepi. Aku masih dalam kota itu. Aku terperangkap selamanya dalam kenangan manis. Aku tak bisa melangkah kedepan karena aku ada dalam tempurungku. Aku takut keluar, aku takut tak aman. Amarahku membesar, menyambar, menghanguskan. Aku melihatmu disisiku, terpanggang mengerang. Aku melihat sekelilingku, kota ini pun perlahan memerah, asap tebal bergulung naik mengungguli mega. Hanya hitam, putih dan merah. Apiku menghasilkan asap mengandung marah, sesak, takut dan pasrah. Mereka pun terpanggang, ketidakpedulian mereka melenyapkan. Maafkan aku renjana. Aku hanya tak ingin kau diambil orang, aku tak ingin kota kita disesaki kenangan orang-orang. Aku ingin aku, kamu dan kota ini ada serupa seperti ingatanku. Apiku masih menyala!
Tes…! Tes…! Rintik hujan perlahan membasahiku. Aku melangkahkan kakiku mencari lindungan atap seiring dengan jiwaku kembali pada ragaku kini. Syukurlah, semua hanya angan. Kota ini memang maha membolak-balikkan kesadaran. Aku beruntung tak diberi kemampuan menjadi-nyatakan semua inginku. Kini aku sepenuhnya sadar, delapan tahun sudah kota ini, kamu dan mereka telah mengubah hidupku dengan seizinku. Kota ini, biarlah menyimpan semua memori aku, kamu dan mereka. Kita. Karena hidup nyataku, usahaku mengenal diriku, mengenalmu dan mengenal mereka lebih indah saat ini. Kini aku kuat tanpa harus selalu keras. Terima kasih renjana karena telah perlahan membantuku membuka sayapku, walau awalnya rapuh, namun kini aku bisa mengepak tanpa takut terjatuh. Aku percaya kamu akan selalu ada buatku, sampai titik ini bukankah cinta harus dipertahankan? Amarahku pun, seperti saat di kota ini, mereda dan aku berusaha terus mengendalikannya walau sering tak berhasil. Aku, kamu, kota ini, renjana tak mengukir duka. Manusia boleh berencana, Tuhan yang akan membukakan jalan-Nya.
Maka berilah kami rejeki hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Karya: Laurentia Henrieta PSP